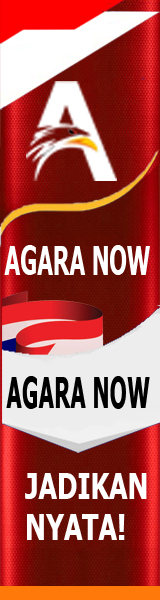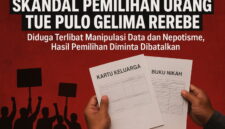Kutacane – Stadion H. Syahadat, Kutacane, Aceh Tenggara, yang semestinya menjadi ruang hiburan rakyat, mendadak berubah menjadi arena kematian. Pada malam penutupan konser Faul Gayo dalam rangkaian Muslim Ayub Festival, seorang pemuda bernama Nanda, 21 tahun, tewas ditikam orang tak dikenal. Musik yang riuh, sorak sorai penonton, dan dentuman lampu panggung seketika terhenti oleh jeritan, darah, dan kepanikan.
Tragedi ini bukan sekadar catatan kriminal. Ia adalah alarm keras tentang betapa rapuhnya ketaatan pada syariat di tanah yang seharusnya tegak menjunjung marwah Islam. Aceh bukan daerah biasa. Ia diberi kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ulama, lewat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan. Fatwa itu tegas: tidak boleh ada pertunjukan seni budaya yang melanggar syariat, termasuk konser musik yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, menghadirkan alat musik terlarang, atau digelar di waktu yang mengganggu ibadah.
Namun, di Kutacane, semua batas itu diterabas. Penonton bercampur tanpa sekat, suasana bergelimang pesta, dan musik menghentak hingga larut malam mendekati pukul 11. Apa yang diperingatkan ulama justru diabaikan. Fatwa dijadikan kertas tak bernilai, syariat dilanggar terang-terangan, dan adat Tanoh Alas yang menjunjung kesopanan seolah ditukar dengan dentuman panggung.
Ketua Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahrinsyah, bicara lantang. “Ini bukan hanya soal satu nyawa yang melayang. Ini adalah bukti nyata bahwa fatwa ulama tidak dihormati, syariat dianggap sepele, dan kita semua lalai menjaga marwah Aceh Tenggara,” katanya, Selasa, 19 Agustus 2025.
Dahrinsyah menuding keras Muslim Ayub, anggota DPR RI sekaligus inisiator festival, yang menurutnya tak bisa cuci tangan. Seorang wakil rakyat, katanya, seharusnya menjadi teladan moral, bukan justru pembuka jalan bagi hiburan yang melanggar aturan ulama dan syariat. “Hiburan memang hak masyarakat, tapi hiburan yang menjerumuskan umat pada mudharat jelas tidak bisa dibenarkan,” ucapnya.
Bagi Dahrinsyah, tragedi ini adalah pelajaran pahit bahwa ketika ulama dipinggirkan, yang lahir bukanlah keriangan, melainkan kekacauan. “Untuk apa sebuah konser jika akhirnya berujung darah? Panggung hiburan macam apa yang membuat anak muda pulang tinggal nama?” katanya geram.
Tuntutan pun ia sodorkan tegas: penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas tragedi ini; pemerintah daerah harus memperketat izin hiburan dengan mengacu pada fatwa MPU; dan masyarakat mesti waspada, tidak lagi larut dalam pesta yang merusak nilai agama. “Kita semua harus berani bertanya: apakah pantas syariat kita ditukar dengan gemerlap lampu panggung?” ujar Dahrinsyah.
Kini, duka sudah tercatat. Satu keluarga kehilangan anak, Aceh Tenggara kehilangan marwah, dan publik kehilangan rasa aman. Jika tragedi ini hanya berakhir sebagai kabar musiman, maka sejarah akan menulis kita sebagai generasi yang rela menukar darah dan nyawa demi euforia sesaat.
“Tragedi ini harus jadi momentum kebangkitan moral. Kalau tidak, kita akan dikenang sebagai bangsa yang membiarkan darah tertumpah hanya karena konser,” pungkas Dahrinsyah.
Laporan : Salihan Beruh/TIM